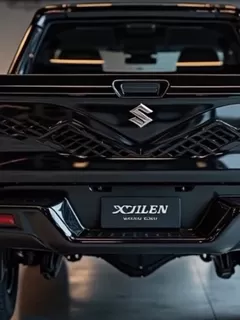Oleh : Dr. Siti Zahara Nasution, S. Kp., MNS & Putra Jaya Hulu, S.Kep.,Ns
(Program Studi Magister Ilmu Keperawatan F.Kep.USU)
Realitasonline.id - Di tengah gemuruh kemajuan teknologi medis—mulai dari robot bedah canggih, sistem diagnostik berbasis kecerdasan buatan, hingga telemedicine yang menghubungkan pasien dengan dokter lintas benua—sebuah pertanyaan
fundamental kembali mengemuka: "Apakah pelayanan kesehatan masih memiliki hati?" Ketika mesin semakin pintar dan prosedur medis semakin presisi, justru di situlah filsafat keperawatan menjadi kompas moral yang memastikan bahwa kemanusiaan tidak hilang di balik layar monitor dan algoritma rumit.
Ketika Teknologi Bertemu Kemanusiaan
Rumah sakit modern hari ini dipenuhi peralatan canggih yang mampu membaca
kondisi pasien dalam hitungan detik. Sensor pintar memantau detak jantung,
tekanan darah, saturasi oksigen— semuanya terekam digital, terukur, dan teranalisis. Namun, tidak ada satu pun alat yang mampu mengukur ketakutan seorang ibu yang menunggu hasil operasi anaknya, atau keputusasaan seorang lansia yang merasa menjadi beban keluarga. Di sinilah filsafat keperawatan memainkan perannya yang paling krusial: mengembalikan wajah manusiawi pada sistem kesehatan yang semakin teknis.
Baca Juga: Etika di Meja Operasi: Ketika Kesunyian Menjadi Tanggung Jawab Moral Perawat Bedah
Filsafat keperawatan mengajarkan bahwa setiap pasien bukan sekadar diagnosis
medis yang harus "diperbaiki," tetapi manusia utuh dengan cerita hidup, ketakutan, harapan, dan martabat yang harus dijaga. Ini bukan romantisme usang—ini adalah landasan etis yang membedakan pelayanan kesehatan yang beradab dengan sekadar transaksi medis.
Tiga Pilar Filosofis yang Tidak Dapat Digantikan Mesin
Pertama, dimensi ontologis keperawatan memandang manusia sebagai makhluk
holistik—bukan hanya tubuh yang sakit, tetapi pribadi dengan pikiran, emosi, nilai
spiritual, dan konteks sosial budaya. Ketika seorang perawat duduk mendengarkan
keluhan pasien penderita kanker tentang ketakutannya meninggalkan anak-anak
yatim, ia tidak sedang "membuang waktu"—ia sedang melakukan intervensi
terapeutik yang berbasis pada pemahaman mendalam tentang hakikat manusia.
Kedua, dimensi epistemologis menunjukkan bahwa keperawatan membangun pengetahuannya dari riset ilmiah yang ketat, teori-teori global yang teruji, dan praktik berbasis bukti. Jean Watson dengan teori caring-nya, Dorothea Orem dengan konsep self-care, atau Peplau dengan hubungan interpersonal terapeutik—semua ini adalah kontribusi ilmiah keperawatan yang memberikan kerangka kerja dalam merawat dengan penuh makna.
Ketiga, dimensi aksiologis menempatkan etika dan nilai kemanusiaan sebagai inti
dari setiap tindakan. Di era ketika efisiensi dan profit kerap menjadi ukuran
kesuksesan rumah sakit, filsafat keperawatan mengingatkan bahwa nilai tertinggi adalah martabat manusia—bukan angka statistik atau target operasional.
Baca Juga: KENALI GEJALA AWAL PENYAKIT JANTUNG KORONER SEBELUM TERLAMBAT
Dilema Etis di Era Digital
Bayangkan sebuah skenario: sistem AI di rumah sakit menyarankan untuk menghentikan perawatan intensif pada pasien usia lanjut karena "analisis cost benefit menunjukkan hasil tidak optimal. "Siapa yang akan mempertanyakan rekomendasi algoritma tersebut? Siapa yang akan berdiri membela hak pasien untuk tetap diperjuangkan kesembuhannya? Jawabannya adalah perawat yang memiliki landasan filosofis kuat tentang nilai hidup manusia.
Filsafat keperawatan mengajarkan bahwa setiap kehidupan memiliki nilai intrinsik
yang tidak bisa direduksi menjadi perhitungan matematis. Keputusan klinis tidak boleh hanya didasarkan pada data— tetapi juga pada kebijaksanaan, empati, dan pemahaman konteks kehidupan pasien secara utuh.